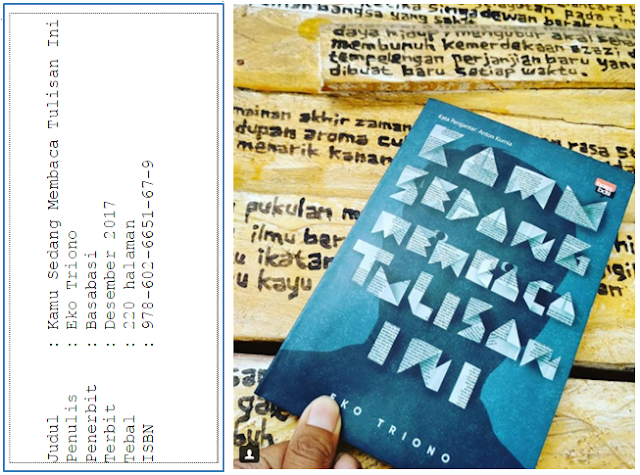|
| image by biem.co |
Sejak kecil, ayah selalu mengajarkanku bersedekah secara diam-diam. Jadi jangan heran ketika di lipatan bukumu, di dalam saku baju, di selipan tas yang biasa kau bawa, atau beberapa meter di depanmu akan kau temukan beberapa lembaran uang kertas atau benda berharga lainnya. Kau tak perlu tahu siapa orang yang menaruh semua hal itu, kau cukup mengambilnya dan meyakini kalau ia adalah sebuah keajaiban; sebuah hadiah dari Tuhan untukmu.
Selain itu, ayah selalu memberikan
saran-sarannya di pagi hari. Seperti ketika aku berusia 7 tahun dan hendak
masuk sekolah untuk pertama kalinya. “Jadilah anak yang berbakti. Taati
apa yang guru katakan padamu, jangan melawannya.” Aku ingat betul pesan itu
bahkan hingga saat ini.
Ayah adalah lelaki yang akan kujadikan
panutan. Aku ingin seperti ayah. Begitu ambisius sampai di suatu ketika, aku
menemukan ayah, yang aku tahu kemudian, dalam keadaan mabuk. Ia menggebuk pintu
kuat-kuat dan meminta ibu bergegas membukanya.
Malam itu aku terbangun oleh suara gaduh
yang ditimbulkan Ayah.
“Ayah kenapa, Bu?” Aku nyaris menangis
lantaran mengkhawatirkan keadaan ayah.
“Ayah cuma kecapaian. Kamu tidur lagi saja,
ayah sedang butuh istirahat,” jawab Ibu, yang kalau kukenang hari ini, suaranya
terdengar begitu lirih.
Aku kembali ke kamar, tapi tidak langsung
tidur. Menjadi anak satu-satunya membuat aku merasa kesepian di saat seperti
ini. Ibu tengah menemani ayah, sedangkan aku sendirian di dalam kamar. Pikiranku
melompat-lompat, kemudian bertanya, apa bakal seperti itu kalau menjadi seorang
ayah?
Beberapa tahun setelahnya, aku meyakini
kalau ayah senang mabuk-mabukan setelah ia diangkat sebagai Walikota. Aku
merasakan dampaknya hingga di jabatannya yang kedua. Ayah jadi semakin jarang
pulang, jarang mengajakku jalan-jalan, dan lebih sering saat sampai rumah ia
meluapkan kemarahannya pada aku dan ibu. Ayah jadi tempramen dan begitu
sensitif pada hal-hal yang dianggapnya tidak beres. Padahal kami sama-sama
tahu, ayah sedang ada masalah di pekerjaannya.
Satu hal yang paling kuingat betul, ketika
hati ayah sedang stabil, ia memanggilku untuk bertemu di ruang kerjanya. Aku
penasaran, ada apa?
“Kenapa takut-takut seperti itu? Aku
ayahmu, Nak.”
“Aku tidak takut, aku hanya khawatir
mengganggu kesibukan Ayah.” Baiklah, aku berusaha untuk tidak berbohong.
“Bicara apa kamu, Nak, mana mungkin Ayah setega
itu pada anak semata wayangnya.” Ayah berdiri dan menghampiriku yang mematung di
depan pintu, “maafkan Ayah kalau banyak menghabiskan waktu di tempat kerja.
Kamu sudah beranjak remaja, Nak. Rasa-rasanya, baru kemarin Ayah mengajarkanmu
naik sepeda,” kenang Ayah.
Kenapa ayah harus berkata seperti itu?
Memori lamaku, di ruangan kerja ayah, kembali terbuka. Ibarat proyektor, ia
memancarkan cahaya di atas kepala dan mengeluarkan siluet aku dan ayah yang
saling bertukar tawa. Sesekali aku terisak lantaran ayah melepaskan stang
sepeda sebelum aku betul-betul siap. Di kali lain aku terbahak, sebab saking
semangatnya, ayah terus melaju mendorong sepedaku dari belakang, sampai ia
tidak melihat ada lubang di jalan raya, di hadapan kakinya. Ia hilang
keseimbangan, lalu tersungkur. Buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Begitu
pepatah berujar. Saat ayah jatuh, tak lama aku pun menyusulnya. Terjungkal dari
jok sepeda. Lepas itu kami membiarkan tawa merajai jiwa masing-masing, seolah
tiada kebahagiaan hakiki selain hari itu.
Ah, waktu yang telah lalu. Akankah ia
kembali?
“Ada yang ingin Ayah sampaikan kepadamu.”
“Katakan saja, Ayah. Aku akan selalu setia
mendengarnya.”
“Kau anak yang baik. Harapan kami
satu-satunya.” Entah ke mana arah ucapan ayah saat itu, aku belum menangkapnya.
“Sudah hampir lima tahun Ayah menjabat Walikota. Ayah sangat mengharapkan ada
yang meneruskannya.”
“Bukankah Ayah akan mencalonkan diri
lagi?” meski mulanya aku tidak peduli, toh aku tetap tahu berita itu.
“Tentu saja, dan Ayah yakin akan terpilih
lagi. Tapi setelahnya? Akan amat disayangkan kalau apa yang sudah Ayah lakukan
tidak bisa selesai dan jatuh di tangan orang lain.”
“Aku belum siap. Aku tidak tertarik
sedikit pun,” kataku akhirnya.
“Kenapa?” tanya Ayah gegas.
“Aku tidak ingin anak-anakku, di kemudian
hari, merasakan apa yang aku rasakan sekarang.” Aku berusaha untuk tidak
terdengar menyedihkan.
“Kamu lekaslah ikut Ayah. Ada yang harus
Ayah tunjukkan.”
Sebaris kalimat itu yang di hari depan
membuat aku benar-benar menyesal mengidolakan Ayah. Aku menuruti ke mana ayah
mengajakku pergi. Dengan mobil dinas miliknya, aku dibawa keliling kota.
Mulanya aku mengira akan diajak berjalan-jalan di taman kota yang baru
diresmikannya—sebuah alun-alun yang diidam-idamkan warganya sejak lama. Orang
tua teman-temanku pernah berkata, ayah melakukan rekonstruksi jalan raya dan
pembangunan taman kota hanya untuk mengambil hati warga kotanya agar memberikan
suara untuk melanggengkan ia kembali menjabat sebagai orang nomor satu di kota
kami. Aku tahu mereka pura-pura tidak berkata seperti itu ketika aku melintas,
tetapi, sepelan apapun, selama ia sedang membicarakan ayah, aku bisa
mendengarnya.
“Turunlah,” ucap Ayah sesaat setelah
membukakan pintu. Ia persis seperti Mang Yadi, sopir pribadi yang kali ini
sengaja tidak ayah ajak.
Aku turun dari mobil tanpa harapan apa-apa.
Aku pastikan dengan melihat sekeliling, sedang di mana kami saat itu?
Belasan tahun aku hidup dan tinggal di
kota ini, baru sekarang, kataku saat itu, melihat rumah-rumah kumuh; rumah
kardus, rumah bambu, rumah tak layak tinggal berderet.
“Ini di mana? Aku tidak pernah kemari,
Ayah....”
Ayah menyebut sebuah nama kampung, yang
sangat asing di pendengaranku. “Di kampung inilah banyak Ayah temui orang-orang
yang butuh bantuan kita. Tidakkah kamu berpikir untuk berbagi kebahagiaan
dengan mereka?”
Aku tidak lekas menjawab. Mataku
membelalak. Tanpa bermaksud menyinggung, ini seperti sarang para pengemis.
Orang-orang kumuh yang biasa minta-minta ke rumah ternyata ada di kampung ini.
Mungkinkah ini alasan ayah pulang larut malam bahkan sampai berminggu-minggu
tidak bertemu dengan aku dan ibu? Mungkinkah ini alasan ayah ingin terus
menjabat sebagai Walikota? Ada sedikit rasa yang timbul, dan membuat aku
berpikir ulang tentang tawarannya.
“Bantu Ayah ambil bingkisan di dalam
mobil, Nak.” Tanpa membuang waktu, aku turuti apa kata ayah. Entah kapan ia
menyiapkan buku-buku tulis, kue-kue, pakaian dan banyak lagi. Aku juga menemukan
amplop berisi uang. Saat itu, kami memang tidak memakai pakaian mencolok. Tak
ada juga ajudan ayah menyertai. Jadi wajar bila orang-orang yang sibuk mengais
makan di tempat sampah, seorang gadis menjemur pakaian, anak-anak bermain
kejar-kejaran, seorang ibu menyusui bayinya di pinggir jalan itu tidak begitu
memerhatikan kehadiran kami. Mobil pun sengaja ayah parkir agak jauh dari depan
gang perkampungan.
“Taruhlah bingkisan itu di manapun kamu
mau. Ayah akan menunjukkan padamu apa itu sedekah sirri.”
“Sir..? Sir apa, Yah?”
“Sedekah Sirri, artinya sedekah sembunyi-sembunyi. Orang-orang tidak boleh
tahu kalau kita yang memberikannya.” Ayah berupaya menjelaskan sesederhana
mungkin.
“Memangnya kenapa kalau mereka tahu?”
“Kamu juga nanti akan tahu sendiri.
Lakukanlah dulu. Ikuti apa kata Ayah.” Ayah memberikan senyum paling tulusnya.
Itulah yang akan aku kenang kemudian hari ketika ayah wafat karena penyakit kankernya.
“Cobalah taruh di belakang rumah itu, yang
tidak ada orangnya,” tunjuk Ayah pada rumah berdinding kayu. Aku menduga
penghuninya sedang bekerja. Segera aku berjalan, melihat-lihat sekitar—untuk
memastikan tidak ada yang memerhatikan perbuatanku—, lalu gegas meletakkannya.
Tidak lama berselang, ketika kami mulai
sembunyi di balik salah satu rumah, ada seorang bapak yang menemukannya. Ia
tampak bahagia sekali. Langsung menaruh di dalam karung goni di balik
punggungnya. Ia lekas membawanya berlari menuju rumah yang di sana ada seorang
bocah melompat kegirangan. Kupikir bukan karena ia tahu ayahnya menemukan bingkisan
dari kami, tetapi karena orang yang ia tunggu-tunggu akhirnya pulang juga. Sama
seperti aku, setiap kali ayah pulang, ia selalu membawa mainan, tetapi nyaris
bukan itu alasan aku gembira menyambutnya.
“Bagaimana?” tanya ayah tiba-tiba. Aku
tidak tahu apakah yang ia maksudkan sama dengan apa yang aku tangkap waktu itu.
Namun, aku menjawabnya, “Seru, Ayah. Seperti main game!”
“Kamu suka?”
“Suka banget, Ayah!”
Setelah hari itu, Ayah semakin gencar menanamkan
pengetahuan padaku, kalau dengan menjadi seorang pemimpin, apa pun bisa
dilakukan.
***
Sejujurnya, aku tidak begitu ingin menjadi seperti
sekarang. Terlebih ketika beberapa tahun lalu, setelah pengalaman mengunjungi
kampung kumuh itu, aku seperti menjadi pribadi yang berbeda.
“Kamu tunggu saja dulu di mobil, Ayah ada perlu. Tidak
lama,” ucap Ayah suatu hari. Bisa saja saat itu aku pulang sendiri atau
menyetir sendiri. Ayah kebetulan saja sedang ada di rumah dan sengaja ingin
menjemputku yang baru pulang dari Singapura. Aku habis berlibur dengan kawan-kawan
kampus. Namun aku menurut saja untuk ia jemput dan menunggunya di dalam mobil
ketika kami berhenti di sebuah hotel. Lagi pula, saat itu badanku sedang
kelelehan sekali.
“Urusannya akan menjadi rumit kalau Pak Wali sudah
ikut campur,” desas-desus itu kudengar melalui orang yang melintas di depan
mobil baru Ayah. Barangkali ia tidak menyadari kalau ada anaknya yang
mendengarkan. Ia dan seorang temannya yang juga berjas rapi, gegas memasuki
pintu hotel dan menurut perkiraanku, ia menuju ke ruangan yang juga dituju oleh
ayah.
Sewaktu aku baru menyalakan aplikasi musik di
ponselku, ayah menelepon.
“Kamu pulang saja lebih dulu, Ayah sudah menghubungi
Pak Yadi untuk menjemputmu. Sebentar lagi dia datang,” katanya tergesa-gesa.
“Ayah....” telepon sudah terputus. Ah, kenapa ayah
masih menganggapku seperti anak kecil! Ingin aku keluar dari mobil dan langsung
mencari taksi, tapi sial, Pak Yadi lebih dulu melihatku. Ia menekan klakson dua
kali dan menyebut namaku satu kali.
***
Barangkali, inilah yang kemudian ayah rasakan. Aku
berhasil menjabat sebagai Walikota untuk kedua kalinya, setelah ayah. Kau
tahulah, selalu ada campur tangan ayah dan partai yang membesarkannya. Betapa
bangga Ayah, sepertinya, meskipun ia tidak bisa menghadiri pelantikanku saat
itu. Ia telah wafat bulan lalu setelah beberapa tahun mendekam di penjara, di
jabatanku yang pertama. Pada akhirnya, setelah hidup di lingkungan baru ini,
aku tahu satu hal: menjadi pejabat pemerintah bukan lagi soal korupsi atau
tidak, tetapi sudah ketahuan atau belum. Sebab, itulah yang mendera ayah—juga
aku. Aku sudah telanjur kejebur di sebuah sumur berlendir, berbau busuk tanpa
pelita dan pegangan. Dan lagi, Satu hal yang lupa aku ceritakan di awal; selain
ayah mengajarkanku bersedekah secara diam-diam, ia juga
memberitahuku cara korupsi, memberi dan menerima suap secara diam-diam.
Di ruangan yang pengap ini, aku hanya
ingin bertanya: apa kabar anakku di rumah?
Cilegon, 7102017
*) pernah dimuat di biem.co: Pesan Ayah - Ade Ubaidil